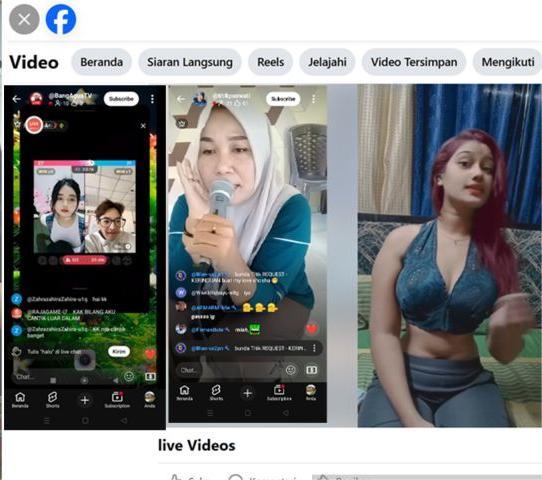JAKARTA, borneoreview.co – Di tengah dunia yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian, satu hal tetap menjadi kebutuhan paling dasar dan tak tergantikan, yaitu pangan.
Dalam konteks Indonesia, pembicaraan soal ketahanan pangan tidak lagi cukup hanya berbicara tentang panen dan produksi beras.
Isu ini sudah berkembang menjadi persoalan sistemik, menyangkut keadilan akses, keberlanjutan produksi, serta martabat bangsa dalam menjaga kedaulatannya.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau.
Artinya, ketahanan pangan tidak hanya bisa dinilai dari seberapa banyak hasil panen, melainkan dari bagaimana pangan tersedia dan bisa diakses oleh setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, ada kabar baik dari sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada triwulan pertama 2025, sektor ini tumbuh paling tinggi dibanding sektor lain, dengan kontribusi sebesar 10,52 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Produksi padi meningkat 51,45 persen, sementara jagung tumbuh 39,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi indikator positif bahwa upaya revitalisasi pertanian mulai menunjukkan hasil.
Lebih menggembirakan lagi, cadangan beras pemerintah tercatat mencapai 3,5 juta ton, angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
Hal yang patut diapresiasi, seluruh penyerapan beras oleh Bulog hingga Mei 2025 sebanyak 1,8 juta ton, berasal dari produksi dalam negeri.
Ini menunjukkan bahwa petani kita mampu memenuhi kebutuhan nasional, tanpa harus mengandalkan impor untuk kategori beras medium.
Produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Maret 2025, bahkan tercatat mencapai 8,67 juta ton, meningkat lebih dari 52 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan ini disebabkan oleh meluasnya areal panen yang kini mencapai 2,83 juta hektare. Proyeksi BPS menyebutkan bahwa total produksi beras hingga Agustus 2025 bisa mencapai hampir 25 juta ton.
Ini memberi ruang optimisme, tetapi juga tanggung jawab, yakni bagaimana menjaga momentum ini agar tidak hanya berumur pendek.
Di sisi lain, kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP), indikator yang menggambarkan daya beli petani, terus mengalami peningkatan. Pada Januari 2025, NTP berada di angka 123,68, naik 0,73 persen dari bulan sebelumnya.
Angka ini berarti penghasilan petani lebih tinggi dibanding pengeluaran konsumsi rumah tangga pertanian, sebuah sinyal bahwa sektor ini mulai memberikan imbal hasil yang lebih baik bagi pelaku utamanya.
Meskipun demikian, tidak semua berjalan mulus. Tantangan klasik masih menghantui, seperti alih fungsi lahan produktif, distribusi hasil tani yang belum merata, serta ketergantungan terhadap impor komoditas tertentu.
Belum lagi ancaman perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi dan bisa mengganggu siklus tanam maupun pasokan air irigasi.
Sektor pertanian sendiri masih menjadi penopang utama lapangan kerja nasional. Data BPS Februari 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 41 juta orang atau sekitar 28 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor ini.
Dalam satu tahun terakhir, terjadi penambahan hampir 900 ribu tenaga kerja di bidang pertanian. Ini memperlihatkan bahwa sektor ini masih menjadi tumpuan bagi banyak keluarga, terutama di perdesaan.
Melihat capaian dan tantangan yang ada, ketahanan pangan jelas bukan isu yang bisa diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Kita perlu berpikir sistemik dan melibatkan berbagai sektor.
Pertama, penguatan infrastruktur dasar dan kelembagaan pertanian menjadi sangat penting. Irigasi yang andal, gudang penyimpanan yang layak, akses jalan ke pasar, serta keberadaan koperasi.
Juga kelompok tani yang aktif akan memperbaiki posisi tawar petani, sekaligus menekan kerugian pascapanen.
Kedua, kita perlu serius dalam mendorong diversifikasi pangan. Ketergantungan berlebihan pada beras membuat sistem pangan kita rentan.
Padahal, Indonesia kaya akan pangan lokal, seperti singkong, jagung, sagu, dan berbagai jenis umbi-umbian.
Mendorong konsumsi pangan lokal, baik lewat insentif produksi maupun kampanye publik, bisa memperkuat ketahanan pangan dari sisi konsumsi.
Ketiga, teknologi digital harus dimanfaatkan secara lebih luas. Banyak petani kini sudah menggunakan aplikasi cuaca dan informasi harga pasar, namun kesenjangan digital masih cukup besar.
Perlu pelatihan, pendampingan, dan akses perangkat yang merata agar manfaat teknologi benar-benar dirasakan hingga ke petani kecil.
Keempat, keberadaan cadangan pangan nasional yang cukup harus disertai sistem distribusi dan perlindungan sosial yang tanggap krisis.
Pengelolaan cadangan tidak bisa hanya administratif, tapi harus berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam kondisi darurat, waktu menjadi faktor penentu, bantuan pangan harus sampai ke tangan yang tepat dalam waktu yang cepat.
Kelima, aspek yang sering luput adalah edukasi konsumsi dan literasi gizi. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa pilihan makan sehari-hari punya dampak terhadap sistem pangan nasional.
Mengonsumsi makanan yang beragam dan tidak berlebihan, serta menghindari pemborosan, merupakan kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan.
Semua ini kembali pada satu hal, ketahanan pangan bukanlah urusan teknis semata. Ia adalah cermin dari bagaimana negara melindungi rakyatnya dan bagaimana masyarakat menyadari tanggung jawab kolektifnya.
Presiden pertama RI Soekarno pernah berkata, “Pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa.” Kalimat ini tidak hanya menjadi pengingat sejarah, tapi juga penanda arah.
Bangsa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya akan selalu berada dalam posisi yang rapuh, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial.
Di tengah geliat pertumbuhan produksi yang menggembirakan, kita tetap perlu waspada.
Momentum ini harus dijaga dengan kebijakan yang konsisten, partisipasi masyarakat yang aktif, dan dukungan lintas sektor yang solid. Ketahanan pangan adalah maraton, bukan sprint.
Dibutuhkan visi jangka panjang, kesabaran dalam pelaksanaan, dan kepekaan terhadap perubahan zaman.
Pada akhirnya, ketahanan pangan adalah bentuk nyata dari keberpihakan. Ia berbicara tentang apakah negara hadir di ladang-ladang petani, di meja makan keluarga miskin, dan dalam kebijakan yang mendukung keberlanjutan.
Dan ketika ketahanan pangan benar-benar terwujud, bukan hanya perut yang kenyang, tapi harga diri bangsa pun terangkat.
*) Dr. Nenden Budiarti, S.ST., S.E., M.Si. adalah statistisi Ahli Muda Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik