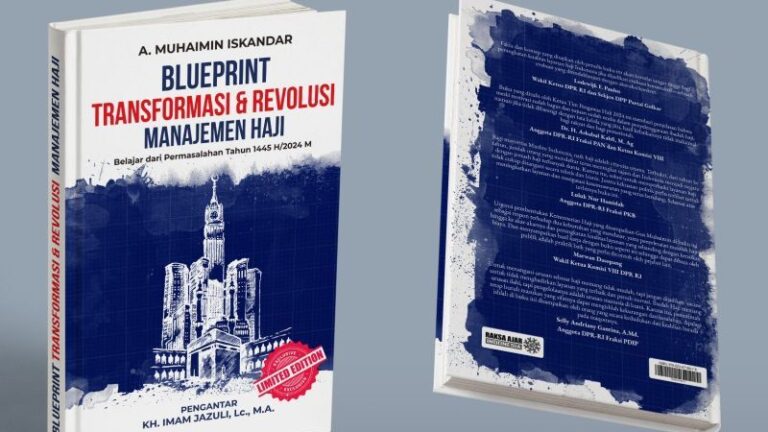JAKARTA, borneorevoew.co – Pagi masih basah oleh embun ketika Syahiri, warga Gebang, Mataram, Nusa Tenggara Barat melangkah tergesa ke pangkalan gas elpiji tiga kilogram di dekat rumahnya.
Dua hari berturut-turut, Syahiri pulang dengan tangan kosong. Tak ada tabung elpiji tiga kilogram yang dibawa.
Harapan sederhana, agar bisa menyalakan kompor untuk sarapan keluarga. Tapi, berulang kali harapan itu pupus di hadapan antrean yang kian panjang.
Cerita Syahiri adalah potret banyak warga lain dari lorong-lorong Kota Mataram, hingga pelosok Lombok Timur.
Yang dalam sepekan terakhir, harus berjibaku mencari tabung gas tiga kilogram.
Fenomena ini bukan hal baru. Setiap momentum tertentu seperti Maulid Nabi, hajatan, atau liburan panjang, kelangkaan elpiji subsidi itu kerap muncul bagai ritual tahunan.
Tabung berwarna hijau itu bukan sekadar energi rumah tangga, melainkan denyut kehidupan keluarga kecil, pedagang gorengan di pinggir jalan, hingga warung nasi dengan margin tipis.
Kehilangan akses gas berarti terhentinya roda usaha dan terganggunya keseharian.
Akar Masalah
Di balik kerumunan antrean, sesungguhnya barang tersedia. Kepala Bidang Bapokting Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida menggambarkan situasi ini sebagai lonjakan permintaan musiman.
Ia menyebut Maulid Nabi serta kembalinya mahasiswa dari liburan semester sebagai pemicu konsumsi di luar pola normal.
Dinas pun mengajukan tambahan 21,3 metrik ton atau setara sekitar 7.000 tabung ke Pertamina.
Secara teori, distribusi elpiji subsidi mengikuti jalur baku yakni dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) menuju agen, lalu ke pangkalan resmi sebelum akhirnya tiba di tangan konsumen.
Namun dalam praktiknya, selalu ada celah. Sebagian tabung tak berakhir di dapur rumah tangga miskin, melainkan menyasar pengecer dengan harga di atas HET.
Bahkan, merembes ke restoran besar atau industri kecil yang seharusnya menggunakan tabung nonsubsidi.
Di Lombok Timur, pejabat Dinas Perdagangan Saipul Wathon mengakui bahwa konsumsi meningkat tajam selama Maulid.
Jika biasanya satu tabung cukup, kali ini banyak rumah tangga menggunakan dua hingga tiga tabung. Dengan pola konsumsi semacam ini, pasokan normal terasa tidak pernah cukup.
Ketika isu kelangkaan merebak, berbagai spekulasi pun muncul. Salah satunya mengaitkan dengan program makan bergizi gratis (MBG).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kelangkaan ini murni akibat lonjakan permintaan musiman, sama seperti kasus yang sempat terjadi di Sumbawa bulan lalu.
Pertamina Patra Niaga, melalui Area Manager Jatimbalinus Ahad Rahedi, memastikan stok sebenarnya aman.
Ia menjelaskan bahwa tambahan pasokan fakultatif sudah dilakukan pada periode Maulid, dan masyarakat diminta membeli langsung di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai HET Rp18 ribu per tabung.
Namun narasi resmi kerap berseberangan dengan kenyataan di lapangan. Konsumen tetap kesulitan mendapat gas.
Pengecer menjual dengan harga Rp21 ribu hingga Rp25 ribu, dan beberapa pangkalan terpaksa membatasi penjualan hanya satu tabung per rumah tangga.
Kontradiksi inilah yang memunculkan persepsi “langka”, meski data distribusi menunjukkan sebaliknya.
Suara Publik
Hariyono, pemilik pangkalan di BTN Sandik Indah, Mataram, menuturkan bahwa ia harus membatasi penjualan karena distribusi berkurang sementara permintaan meningkat. Tanpa pembatasan, stok habis dalam sehari.
Di sisi lain, pedagang kecil seperti Windu, penjual gorengan di pinggir jalan terjepit antara harga beli yang naik di pengecer, dan tuntutan pelanggan yang tetap menginginkan harga wajar.
Situasi ini memperlihatkan jurang antara klaim ketersediaan dan pengalaman nyata warga.
Kelangkaan elpiji tiga kilogram bukan semata soal stok, tetapi soal tata kelola distribusi dan keadilan akses.
Masalah serupa terjadi hampir setiap tahun. Ada pola berulang yang bisa ditarik seperti halnya distribusi masih rawan bocor karena tabung bersubsidi kerap digunakan oleh usaha non-rumah tangga.
Pengawasan di tingkat pengecer juga lemah, harga melambung, sementara aparat umumnya hanya melakukan kontrol hingga pangkalan.
Di sisi lain, supply dan demand sering tidak seimbang pada momen musiman, ketika kebutuhan melonjak tetapi pasokan tambahan datang terlambat.
Kondisi ini diperburuk oleh minimnya digitalisasi data, sebab distribusi belum sepenuhnya berbasis daring sehingga sulit dipantau secara real time.
Semua ini menunjukkan bahwa masalah elpiji subsidi bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan juga soal keberpihakan.
Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, atau justru bocor ke pihak yang lebih mampu?
Solusi Masalah
Salah satu kunci utama ada di distribusi. Pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat perlu lebih tegas mengawasi agar tabung subsidi benar-benar jatuh ke tangan rumah tangga miskin dan usaha mikro.
Sementara itu, usaha menengah ke atas sebaiknya diarahkan menggunakan tabung nonsubsidi yang memang diperuntukkan bagi mereka.
Selain pengawasan, kesadaran masyarakat juga memegang peran penting.
Edukasi tentang penggunaan elpiji perlu diperkuat, terutama agar warga membeli sesuai kebutuhan dan tidak menimbun.
Kebiasaan panik membeli justru memicu kelangkaan yang sebenarnya bisa dihindari.
Dalam jangka panjang, perlu ada opsi energi lain. Usaha kecil menengah misalnya, bisa diarahkan beralih ke tabung 5,5 kilogram atau sumber energi yang lebih stabil.
Transisi seperti ini akan meringankan beban subsidi sekaligus memberi ruang lebih bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tabung tiga kilogram.
Tak kalah penting adalah digitalisasi distribusi. Program Subsidi Tepat yang tengah diuji melalui aplikasi MyPertamina harus dipercepat.
Dengan basis data by name by address (sesuai nama dan alamat), aliran distribusi bisa lebih transparan, akurat, dan peluang kebocoran semakin kecil.
Dan tentu saja, pola tahunan harus diantisipasi lebih dini. Lonjakan permintaan saat Maulid, Ramadhan, atau Lebaran sejatinya bisa diprediksi.
Kuota tambahan mestinya diajukan lebih awal, bukan menunggu antrean panjang terjadi baru mencari solusi.
Refleksi
Elpiji tiga kilogram bukan sekadar tabung gas hijau. Ia adalah simbol keadilan energi di negeri yang masih mencari keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan rakyat kecil.
Setiap kali warga harus antre berjam-jam atau membayar lebih mahal, persoalan yang muncul bukan hanya soal logistik, melainkan keberpihakan.
Kelangkaan musiman seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola subsidi, memperkuat pengawasan, dan menghadirkan kebijakan yang lebih pro-rakyat.
Energi, pada akhirnya, adalah hak dasar. Menjamin ketersediaannya berarti menjaga denyut kehidupan sehari-hari masyarakat.
Karena bagi banyak keluarga kecil, satu tabung elpiji tiga kilogram bukan sekadar angka di laporan kuota, melainkan nyala api di dapur.
Nyala itu memastikan anak-anak tetap bisa makan, pedagang kecil bisa berjualan, dan roda kehidupan tetap berputar.***