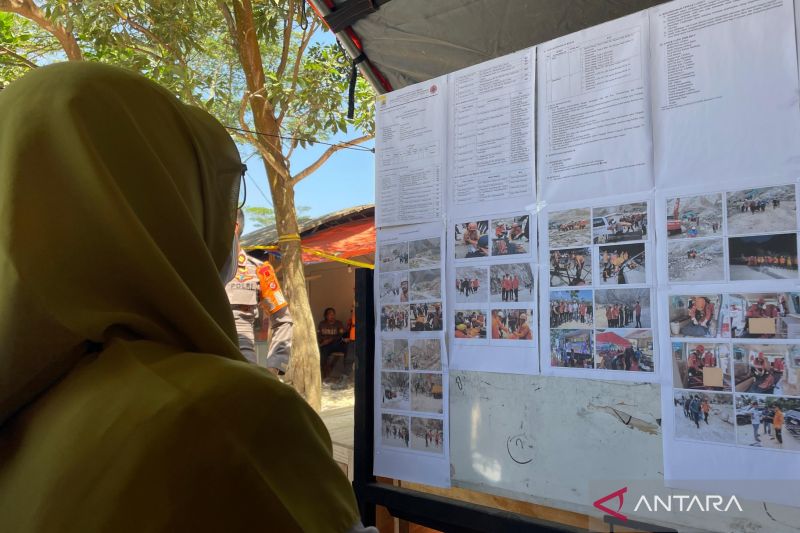MATARAM, Borneoreview.co – Sumbawa Barat bukan hanya tanah tambang. Ia adalah ruang hidup dengan perbukitan hijau.
Bukit membentang, sungai jernih berliku di antara sawah, dan desa-desa nelayan, menggantungkan hidup dari laut.
Kehadiran pertambangan di tengah lanskap semacam itu selalu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah alam akan tetap terjaga? Apakah generasi mendatang masih bisa menikmati tanah subur dan laut yang kaya?
Pertanyaan-pertanyaan itu sempat tumbuh menjadi keresahan di hati warga. Namun, perlahan mulai hadir jawaban melalui langkah-langkah nyata yang ditempuh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN).
Ada keyakinan yang harus dijalankan: tambang tidak boleh hanya meninggalkan lubang.
Ia harus mewariskan kembali kehidupan yang bisa dijaga bersama, warisan hijau yang tetap tumbuh bahkan setelah produksi berhenti.
Salah satu fokus utama untuk menjalankan keyakinan itu adalah rehabilitasi lahan pasca-tambang.
Area yang sudah selesai dieksplorasi tidak dibiarkan tandus, melainkan dipulihkan dengan menanam pohon, memperbaiki tanah, dan menghidupkan kembali ekosistem.
Sejak 2022, ribuan bibit pohon lokal telah ditanam di lahan bekas tambang.
Jenisnya beragam mulai dari mahoni, gamal, hingga pohon buah yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Proses ini tidak hanya dilakukan oleh pekerja perusahaan, melainkan juga melibatkan warga.
Ada kelompok ibu rumah tangga yang membantu pembibitan, pemuda desa yang ikut menanam, hingga sekolah-sekolah yang mengirimkan siswanya untuk kegiatan edukasi lingkungan.
Awalnya banyak yang ragu. Bekas tambang dianggap sulit dipulihkan. Namun seiring waktu, keraguan berubah menjadi keyakinan ketika pucuk-pucuk hijau mulai tumbuh.
Tanah yang semula gersang perlahan tertutup oleh bayangan pohon muda. Bagi warga, pemandangan itu menghadirkan rasa lega. Ini petanda bahwa lahan bisa kembali hidup.
Air, Limbah, dan Teknologi
Dalam industri pertambangan, isu lingkungan terbesar selalu berkaitan dengan air dan limbah.
Di titik ini perusahaan mencoba menjawab dengan teknologi ramah lingkungan. Air dari proses tambang dipantau ketat, memastikan tidak mencemari sungai maupun laut.
Instalasi pengolahan dibangun agar air limbah bisa didaur ulang dan dipakai kembali dalam operasional, sehingga penggunaan air baru berkurang signifikan.
Langkah ini bukan hanya teknis, tetapi bagian dari konsep ekonomi sirkular di sektor tambang.
Caranya, mengurangi pengambilan air baru, perusahaan ikut menjaga ketersediaan sumber daya bagi masyarakat sekitar.
Upaya serupa juga tampak pada pengembangan energi hijau. Panel surya mulai dipasang di beberapa fasilitas, riset menuju elektrifikasi peralatan berat berjalan, dan efisiensi energi didorong agar jejak karbon berkurang.
Perlahan, praktik pertambangan yang biasanya identik dengan emisi besar diarahkan menuju operasi yang lebih berkelanjutan.
Tidak hanya lahan tambang yang dipulihkan, ekosistem di sekitarnya juga dirawat. Di pesisir, konservasi mangrove digalakkan bekerja sama dengan kelompok nelayan.
Mangrove dipandang sebagai benteng alami yang melindungi desa dari abrasi sekaligus rumah bagi ribuan biota laut.
Sementara itu, di perbukitan, warga mengikuti kegiatan menanam kembali pohon pelindung untuk mencegah erosi.
Anak-anak sekolah ikut dalam program penanaman, menjadikannya bagian dari pendidikan lingkungan.
Mereka belajar bahwa menjaga bumi bukan sekadar teori di buku, melainkan tindakan nyata yang bisa dilakukan sejak dini.
Perubahan pun mulai terasa. Sungai yang dulu keruh kini lebih terpantau bersih. Nelayan kembali menemukan kestabilan dalam hasil tangkapan.
Petani di sekitar tambang tidak lagi khawatir lahannya kekeringan karena akses air semakin baik.
Bagi masyarakat, rehabilitasi semacam ini bukan hanya program perusahaan, tetapi jaminan bagi masa depan anak cucu mereka.
Jalan Panjang Keberlanjutan
Meski hasilnya mulai terlihat, jalan menuju keberlanjutan tetap panjang. Rehabilitasi lahan membutuhkan waktu puluhan tahun.
Pohon-pohon yang baru ditanam belum langsung memberikan manfaat. Limbah tambang pun menuntut pemantauan jangka panjang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Tantangan lain datang dari kesadaran masyarakat. Tidak semua warga peduli pada kelestarian lingkungan.
Masih ada yang menebang pohon sembarangan atau merusak fasilitas konservasi.
Di sinilah pentingnya pendidikan lingkungan yang berkelanjutan.
Kesadaran tidak bisa dipaksakan, melainkan perlu ditumbuhkan melalui pengetahuan dan pengalaman langsung.
Kolaborasi menjadi kunci. Keberhasilan program hijau tidak bisa dilepaskan dari kerja bersama dengan pemerintah daerah, sekolah, kelompok nelayan, hingga komunitas lokal.
Ada yang menanam, ada yang merawat, ada yang mengawasi. Setiap pihak punya peran yang saling melengkapi.
Melalui kolaborasi, tumbuh rasa kepemilikan. Warga tidak lagi memandang program ini hanya sebagai inisiatif perusahaan, melainkan juga milik mereka.
Rasa memiliki itulah yang memastikan keberlanjutan tidak berhenti pada laporan, tetapi hidup dalam kesadaran kolektif.
Pertambangan sering dituding sebagai perusak alam. Namun kisah di Sumbawa Barat menghadirkan wajah lain yakni tambang yang berusaha memberi warisan hijau.
Di desa-desa lingkar tambang, ibu-ibu kini terbiasa ikut menanam bibit. Anak-anak sekolah mengenal mangrove bukan hanya sebagai istilah biologi, tetapi sebagai pohon yang mereka rawat bersama.
Nelayan kembali percaya diri melaut karena laut terjaga, sementara petani bisa panen di lahan yang dekat dengan tambang.
Semua itu menjadi bukti bahwa keberlanjutan bukan sekadar jargon. Ia nyata, ia hidup, dan ia bisa dicapai ketika industri, pemerintah, dan masyarakat berjalan beriringan.
Jika emas dan tembaga adalah hasil yang diangkat dari perut bumi, maka warisan hijau adalah hasil yang ditanam kembali untuk bumi. Warisan itulah yang akan menjaga Sumbawa Barat tetap hidup, bahkan setelah tambang berhenti beroperasi.
Ketika generasi mendatang menapaki tanah ini, mereka tidak hanya melihat bekas tambang, melainkan juga jejak hijau yang ditinggalkan sebagai tanda bahwa alam pernah dijaga dengan sungguh-sungguh.***